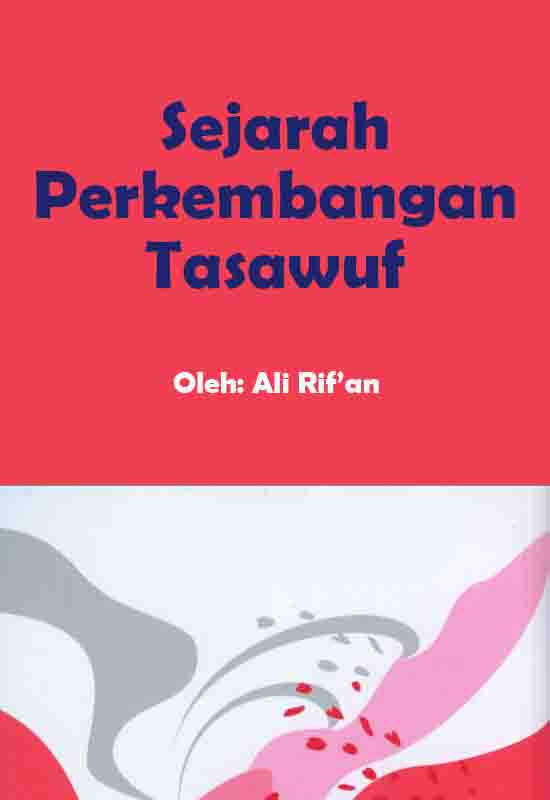4) Tahap Perkembangan Tasawuf
a) Tasawuf Abad Pertama dan Kedua Hijriyah
Menurut para ahli sejarah tasawuf, zuhud atau asketisime merupakan fase yang mendahului lahirnya tasawuf pada abad pertama dan kedua Hijriyah. Dalam Islam, asketisisme mempunyai pengertian khusus. Asketisisme bukanlah kependetaan atau terputusnya kehidupan duniawi, melainkan hikmah pemahaman yang membuat para penganutnya mempunyai pandangan khusus terhadap kehidupan duniawi, di mana mereka tetap bekerja dan berusaha, namun kehidupan duniawi itu tidak menguasai kecenderungan kalbu mereka, serta tidak membuat mereka mengingkari Tuhannya.
Istilah yang populer digunakan pada masa awal tersebut adalah nussaak, zuhhaad dan „ubbaad.
Nussaak merupakan bentuk jamak dari nasik, yang berarti orang-orang yang telah menyediakan dirinya untuk mengerjakan ibadah kepada Tuhan. Zuhhaad adalah bentuk plural dari zahid, yang berarti “tidak ingin” kepada dunia, kemegahan, harta benda dan pangkat. Sedangkan „ubbaad merupakan bentuk jamak dari abid yakni orang-orang yang telah mengabdikan dirinya semata-mata kepada Tuhan.
Para ahli berbeda pendapat mengenai faktor-faktor yang menyebabkan munculnya gerakan asketisisme dalam Islam. R.A. Nicholson berpandangan bahwa asketisisme dalam Islam bersumber dari gerakan Islam itu sendiri, bahkan hasil nyata dari ide Islam tentang Allah, walaupun ada dampak pengaruh agama Masehi (Kristen). Sedangkan Ignaz Goldziher melihatnya melalui dua perspektif. Pertama, asketisisme yang mendekati semangat Islam dan Ahlus Sunnah, sekalipun terkena pula dampak asketisisme Masehi. Kedua, tasawuf dalam pengertiannya yang luas yang berkaitan dengan pengenalan terhadap Allah (ma‟rifah), keadaan ruhaniah (hal), dan rasa (dzauq). Menurutnya yang kedua ini terkena dampak Neo-Platonisme dan ajaran-ajaran Budha ataupun Hindu. Dengan demikian, kedua orientalis di atas menganggap asketisisme dalam Islam muncul dikarenakan dua faktor utama, yaitu Islam itu sendiri dan kependetaan Nasrani, sekalipun keduanya berbeda pendapat tentang sejauh mana dampak faktor yang terakhir
.
Sementara itu, Abu al-Ala Afifi berpendapat bahwa ada empat faktor yang mengembangkan asketisisme dalam Islam.
Pertama, ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Kitab suci Al-Quran sendiri telah mendorong manusia agar hidup saleh, takwa kepada Allah, menghindari dunia beserta hiasannya, memandang rendah hal-hal yang duniawi, dan memandang tinggi kehidupan di akhirat. Selain itu Al-Quran juga menyeru manusia agar beribadah, bertingkah laku baik, salat malam, salat tahajud, berpuasa dan lain-lain.
Kedua, revolusi ruhaniah kaum Muslim terhadap sistem sosio-politik yang berlaku.
Ketiga, karena dampak asketisisme Masehi. Di zaman pra-Islam, menurutnya, bangsa Arab terkena dampak para pendeta Masehi. Dampaknya terhadap para asketis Muslim, setelah timbulnya Islam, masih tetap berlangsung. Namun dampak asketisisme Masehi itu lebih banyak terhadap organisasionalnya ketimbang terhadap aspek prinsipprinsip umumnya.
Keempat, penentangan terhadap fikih dan kalam. Sebagian kaum Muslim yang saleh pada masa itu merasa bahwa pemahaman para fuqaha dan ahli kalam tentang Islam tidak dapat sepenuhnya memuaskan perasaan keagamaan mereka. Sehingga mereka pun mengarah pada tasawuf untuk memenuhi kehausan perasaan keagamaan mereka.
Sedangkan Abu al-Wafa‟ al-Taftazani sendiri, melihatnya secara global dari dua aspek.
Pertama, faktor Al-Quran dan Sunnah. Faktor pertama dan utama yang mengembangkan asketisisme dalam Islam adalah ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan uraian tentang ketidakartian dunia maupun hiasannya, dan perlunya berusaha secara sungguh-sungguh demi akhirat, untuk memperoleh pahala surga ataupun selamat dari azab neraka. Bagi Taftazani, ada banyak ayat tentang kefanaan dunia, serta hamba-hamba Allah yang selalu membersihkan diri.
Kedua, kondisi sosio-politik. Konflik politik yang terjadi sejak akhir masa Khalifah Utsman bin Affan r.a. mempunyai dampak terhadap kehidupan religius, sosial dan politik kaum Muslim. Puncaknya adalah pada zaman dinasti Umayyah yang banyak terjadi kelaliman dan penindasan sehingga banyak orang cenderung pada asketisisme. Kekuasan Bani Umayyah yang juga hidup dalam kemewahan duniawi mengundang reaksi kaum asketisisme yang menginginkan kesederhanaan hidup dan tercipta kesetaraan hidup umat Islam.
Kaum asketisisme pertama ini melihat para Khalifah Umayyah bertingkah laku sama sekali bertentangan dengan kesalehan dan kesederhanaan empat Khalifah yang pertama. Para Khalifah, keluarga dan para pembesar istana hidup dalam kemewahan sebagai akibat dari kekayaan yang diperoleh setelah Islam meluas ke Syria, Mesir, Mesopotamia, dan Persia. Muawiyah telah hidup sebagai raja-raja Roma dan Persia dalam kemewahannya. Di antara Khalifah Bani Umayyah, hanya Khalifah Umar Abdul Aziz (717-720M.) yang dikenal sebagai Khalifah yang mempunyai sifat takwa dan patuh kepada ajaran-ajaran Islam dan sederhana hidupnya.
Khalifah lainnya hidup dalam kemewahan. Khalifah-khalifah Bani Abbas juga demikian, selalu dipenuhi dengan keglamoran hidup dan pertikaian. Melihat fakta-fakta tersebut, orang-orang yang tidak mau terlena dalam hidup kemewahan dan ingin mempertahankan hidup sederhana, menjauhkan diri dari kemewahan dunia tersebut.
Bahkan di antara sebagian sahabat ada juga melakukan protes secara keras, seperti Abu Dzar al-Ghiffari dan Said Ibnu Zubair, sehingga menimbulkan gejolak pada Bani Umayyah.
Era abad pertama dan kedua Hijriyah tersebut sudah banyak para tokoh zahid, baik dari kalangan sahabat maupun generasi tabi‟in. Berikut ini merupakan tokohtokohnya menurut tempat perkembangannya. Para zahid yang tinggal di Madinah dari kalangan sahabat, seperti Abu Ubaidah al-Jarrah (w.18H), Abu Dzar Al-Ghiffari (w 22H), Salman Al-Farisi (w 32 H), dan Abdullah ibn Mas‟ud (w 33 H). Sedangkan dari kalangan tabi‟in, termasuk di antaranya adalah Said ibn Musayyab (w 91 H) dan Salim ibn Abdullah (w 106 H).
Tokoh-tokoh zahid dari Basrah adalah Hasan Al-Bashri ( w 110 H), Malik ibn Dinar (w 131 H), Fadl Al-Raqqasyi, Kahmas ibn Al-Hadan Al-Qais (w 149 H), Shalih Al-Murri dan Abdul Wahid ibn Zaid (w 171 H) dari Abadan. Tokoh-tokoh aliran Kufah adalah Al-Rabi ibn Khasim (w 67 H), Said ibn Jubair (w 96 H), Thawus ibn Kisan (w 106 H), Sufyan Al-Tsauri (w 161 H), Al-Laits ibn Said (w 175 H), Sufyan ibn Uyainah (w 198 H), dan lain-lain.
Sedangkan tokoh-tokoh yang berasal dari Mesir antara lain, adalah Salim Ibn Attar Al-Tajibi (w 75 H), Abdurrahman Al-Hujairah (w 83 H), Nafi‟ hamba sahaya Abdullah ibn Umar (w 117 H), Hayah ibn Syuraih (w 158 H), dan Abu Abdullah ibn Wahhab ibn Muslim Al-Mishri (w 197 H). Pada masa terakhir tahap ini juga muncul tokoh-tokoh, seperti Ibrahim ibn Adham (w 161 H), Fudhail ibn Iyadh (w 187 H), Dawud Al-Tha‟i (w 165 H), dan Rabi‟ah Al-Adawiyyah
.
Menurut Abu al-Wafa‟, aliran asketisisme abad pertama dan kedua hijriyah dapat disimpulkan dengan beberapa karakteristik berikut. Pertama, asketisisme ini berdasarkan ide menjauhi hal-hal duniawi, demi meraih pahala akhirat, dan memelihara dari azab neraka. Ide ini berakar pada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah, dan terkena dampak berbagai kondisi sosio-politik yang berkembang dalam masyarakat Islam ketika itu.
Kedua, asketisisme ini bercorak praktis, dan para pendirinya tidak menaruh perhatian untuk menyusun prinsip-prinsip teoretis atas asketisismenya tersebut. Saranasarana praktisnya merupakan hidup dalam ketenangan dan kesederhanaan secara penuh, sedikit makan maupun minum, banyak beribadah dan mengingat Allah, berlebih-lebih dalam merasa berdosa, tunduk mutlak pada kehendak Allah, dan berserah diri kepadaNya. Dengan begitu, asketisisme ini mengarah pada tujuan moral.
Ketiga, motivasi asketisisme ini adalah rasa takut (khouf), yakni rasa yang muncul dari landasan amal keagamaan secara sungguh-sungguh. Sementara pada akhir abad kedua Hijriyah, di tangan Rabi‟ah al-Adawiyyah, muncul motivasi cinta kepada Allah (mahabatullah), yang bebas dari rasa takut terhadap azab-Nya maupun rasa harap terhadap pahala-Nya. Hal ini mencerminkan penyucian diri dan abstraksi dalam hubungan antara manusia dengan Allah.
Keempat, asketisisme sebagian asketis yang terakhir, khususnya di Khurasan, dan pada Rabia‟ah al-Adawiyyah ditandai kedalaman membuat analisa, yang bisa dipandang sebagai pendahuluan tasawuf. Kelompok ini sekalipun dekat dengan tasawuf, tidak dipandang sebagai para sufi dalam pengertiannya yang terinci. Mereka lebih tepat dipandang sebagai cikal bakal para sufi abad-abad ketiga dan keempat Hijriyah.
 0%
0%
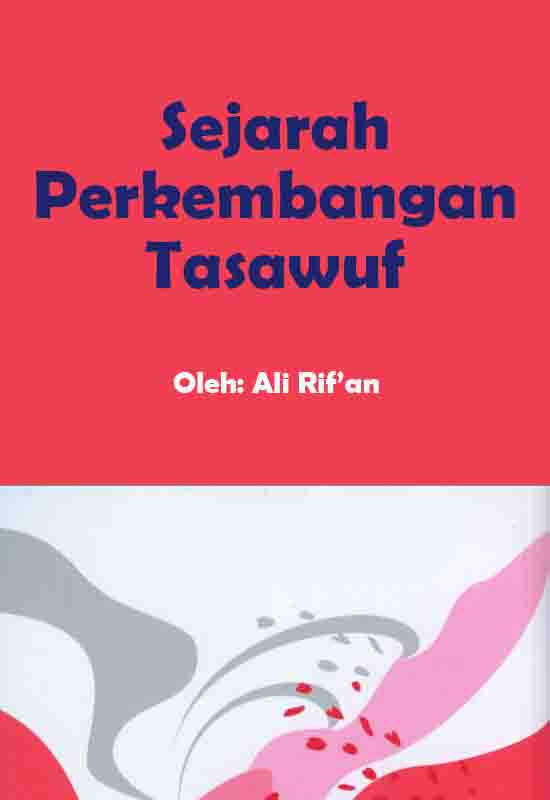 pengarang: Ali Rif'an
pengarang: Ali Rif'an