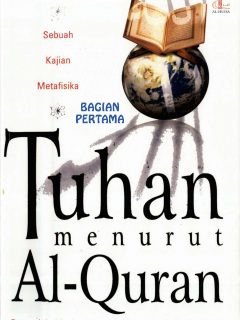Maujud dan Konsep Wujud
Apa yang kita pahami dari kata “eksistensi” (wujud) dan akibat-akibatnya dalam bahasa lain? Dan bagaimana konsep ini merambah ke dalam pikiran kita? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi tema diskusi dalam filsafat Islam selama berabad-abad dan isu-isu yang terkait dengannya telah dianggap sebagai bagian dari pasal-pasal terpenting dalam filsafat.
Siapapun bisa membayangkan bahwa semua pembahasan ini merupakan paparan sia-sia dari isu yang begitu jelas. Akan tetapi, secara bertahap, ia memahami bahwa isu-isu dari realitas wujud, kettinggalan wujud, unitas dan multiplisitas, realitas dan penampakan, dan seterusnya merupakan sebagian dari problem-problem filsafat yang paling pokok. Akan tetapi, problem-problem tersebut tampaknya sederhana namun merupakan isu-isu mendalam dan pelik.
Sebagai suatu contoh dari persentuhan modern dengan isu-isu tersebut, mari kita telaah komentar kritis dari seorang ulama Iran ihwal masalah ini.
Dalam bukunya, Philosophy, Syariat Madari
telah melakukan kajian kritis atas bagian buku Allamah Thabathaba’i, The Principles of Philosophy and the Method of Realism.
Dalam kritiknya, ia menyatakan bahwa pembahasan tentang pemahaman wujud yang analitis dan kesimpulan filosofis dari pemahaman seperti itu, menjadi semacam bahasa permainan sebagaimana dikatakannya: “Allamah Thabathaba’i menganggap wujud sebagai identik dengan realitas dan eksistensi realitas sebagai swabukti.”
Lebih jauh dalam diskusinya, Syariat Madari mengatakan bahwa kini sejumlah persoalan tertanam dalam pikiran mengenai wujud dan realitas sebagai berikut:
Manakah yang swabukti? Maujud ataukah wujud? Apakah manusia menganggap bebatuan, pepohonan, dan manusia sebagai realitas yang swabukti ataukah wujud mereka?
Apakah gagasan bahwa kita tidak bisa menangkap realitas wujud, namun pada saat yang sama karena kita mengetahuinya dengan demikian wujud pada dirinya sendiri, merupakan swabukti bagi kita?
Sebagaimana telah ditunjukkan, mengapa penangkapan eksistensi merupakan swabukti? Saya bisa menganggap eksistensi saya sendiri sebagai swabukti sebagaimana saya menganggap bahwa objek-objek lain sebagai swabukti. Tapi apabila saya menganalisis diri saya sendiri dan memisahkan dan menggantikan unsur “eksistensi” dari aspek-aspek lain diri saya, maka saya tidak bisa mengatakan bahwa saya telah memahami eksistensi dan pengertiannya dalam pola swabukti. Bisa dikatakan bahwa apa yang tarnpak swabukti adalah maujud (being) dan bukan wujud (existence).
Lebih jauh ia mengatakan:
Mendudukkan dan membenamkan diri sendiri dalam konsep eksistensi dan memainkan permainan bahasa, tidak saja membatasi aktivitas sosial, tetapi juga menghalangi kita dari menyerap realitas-realitas dan mencegah kita dari isu-isu filosofis yang berkembang saat itu. [54]
Dengan demikian, tampak jelas bahwa problem eksistensi, konsepnya, tingkat otentisitasnya, masih merupakan suatu problem serius dalam pemikiran filsafat kontemporer.
Untuk melanjutkan telaahan kita dengan pemahaman yang jernih atas masalah tersebut, pertama-tama kami akan menjawab persoalan-persoalan berikut:
1. Apakah analisis dan sintesis, dalam arti umum, merupakan metode tepat guna mendapatkan pengetauan baru tentang dunia dan realitas-realitas di dalamnya?
2. Apakah persepsi-persepsi mental mereka sendiri, yakni konsep-konsep yang kita miliki dari realitas-realitas yang terjadi di dunia, adalah keabsahan nyata (aktual) dalam menyuguhkan realitas-realitas tersebut?
3. Apakah kata-kata, baik merujuk pada objek-objek nyata (real things) ataupun objek-objek khayali (imaginary things) merupakan serangkaian fakta ataukah bukan? (Ini tentunya dalam sorotan definisi ekspansir menurut realitas bahkan dalam pemanfaatan saintifik dewasa ini).
4. Jika konsep-konsep mental dan kata-kata digunakan untuk menguraikan realitas, terlihat dalam suatu perspektif yang lebih luas, adalah realitas itu sendiri, apakah kajian akademis dan realistik atas realitas tersebut, merupakan aktivitas ilmiah yang bisa membuahkan hasil-hasil yang bermanfaat? Atau, apakah ia hanya merupakan suatu tanggung jawab, dalam format bentuk apapun, permainan bahasa?
Dengan suatu wawasan mendalam terhadap apa yang disebut sekarang ini dengan ilmu-ilmu sosial, siapapun bisa menyimpulkan bahwa mayoritas subjek tersebut semata-mata terkait erat dengan kata-kata dan paduannya, konsep-konsep dan pengertian mental, hubungan mereka satu sama lain atau dengan lingkungan sehari-hari manusia, asal-usul dan pertumbuhan kata-kata, makna-maknanya, atau fenomena manusia lainnya senyata huruf-huruf, kata-kata, dan pengertiannya.
Ketika kita mengapresiasi sosiologi dan penyelidikan pencerahannya serta mengarahkan hasil-hasil penyelidikannya untuk membantu kita memilih rangkaian tindakan terbaik dalam banyak aspek kehidupan kita dan menganggapnya sebagai ilmu yang matang membuahkan hasil-hasil yang bermanfaat, maka mengapa kita harns terkejut bahwa analisis saintifik atas suatu kata, persepsi mental, atau fenomena semacam itu bisa membawa kita pada hasil-hasil filosofis yang berharga dan akurat?
Ketika melalui disiplin linguistik dan filsafat analitis, kita menguji asal-usul dan pertumbuhan kata dan bahasa; hubungan mereka dengan faktor-faktor biologis, internal, ataupun lingkungan seperti kepercayaan, keterikatan emosional, ekonomi, politik, kelas-kelas sosial, kebudayaan, dan seterusnya, sehingga menemukan ratusan rahasia menyangkut kehidupan manusia di planet ini, kemudian melanjutkan langkah untuk memperoleh manfaat praktis dari temuan-temuan ini lewat peningkatan taraf kehidupan manusia dengan pelbagai cara, maka mengapa kita tidak bisa melihat riset akurat dan pasti yang telah dijalankan pada konsep eksistensi, pengertiannya, dan realitas eksternal yang darinya konsep ini diturunkan?
Sekarang, mengingat semua yang telah disebutkan, mari kita kembali pada diskusi tentang konsep “eksistensi” dan pengertiannya dan mencoba mengklarifikasi isu-isu yang dimasukkan dalam sorotan pertanyaan yangdiajukan oleh Syariat Madari, dengan harapan bahwa kita akan tetap aman dari bahaya jatuh dalam ilusi dan permainan bahasa.
Pertama-tama, mari kita mulai dari apa yang kita ketahui perihal. masalah ini:
1. Anggaplah ada gelas minum di atas meja di depan Anda. Sekarang saya bertanya kepada Anda: adakah air di dalam gelas itu? Anda melihat gelas tersebut secara lebih cermat atau untuk meyakinkan, Anda menggoyangkan gelas itu seraya berkata: “Ada air, di dalam gelas” atau “Tidak ada air di dalam gelas.”
2 Nah, sekarang anggaplah ada kompor di sudut ruangan tempat ada duduk. Saya bertanya kepada Anda: “Adakah api di dalam kompor itu?” Anda mendekati kompor itu dan memeriksa isinya secara cermat dan berkata: “Ada api di dalam kompor” alau “tidak ada api di dalam kompor”.
Sekarang, simaklah dua pernyataan berikut: (1) Ada air di dalam gelas; dan (2) Ada api di dalam kompor. Dua pernyataan di atas mengandung kata-kata yang berbeda. Masing-masing kata itu mempunyai pengertiannya sendiri, semisal: “di dalam”, “gelas”, “kompor”, “air”, dan “adalah” (is).
Tak ayal lagi, dengan menggunakan setiap kata-kata ini, Anda tengah mengungkapkan persepsi mental yang pasti yang secara jelas bisa Anda bedakan dari persepsi mental lain. Misalnya: “di dalam” berlawanan dengan “di atas” atau “di samping”, “gelas” atau “kompor” berlawanan dengan objek-objek yang ada, “air” dan “api” berlawanan dengan benda-benda lain, dan “adalah” (is) berlawanan dengan “bukan” (is not) dan seterusnya.
3. Persepsi mental yang Anda ekspresikan dengan kata “di dalam” (in) merupakan hal yang jelas dan secara mudah bisa dibedakan dari “di atas” dan seterusnya. Hal yang sama bisa dikatakan tentang persepsi-persepsi mental yang diungkapkan dengan kata-kata, atau, sehingga jika dengan sesuatu yang lain, se- tidaknya Anda tidak pernah menyalahkan mereka untuk satu sama lain. Ini pun merupakan kasus bagi persepsi-persepsi mental yang dilambangkan dengan kata-kata “api” atau “air”. Ketika Anda memegang segelas air untuk diminum, Anda tidak menunjukkan sedikitpun ketakpastian dalam memakai kata “air” untuk menguraikan isi gelas, atau apabila seseorang benar-benar mengetahui kepingan kayu di atas api dan mulai terbakar, Anda sekali lagi tidak akan memastikan dalam penunjukannya sebagai api. Bahkan, ini memang benar, tidak saja untuk Anda, namun bagi semua manusia lain yang sehat dan waras akal.
4. Sekarang bagaimana tentang kata “adalah” (is)? Sudahkah Anda menggunakan kata ini untuk mengekspresikan suatu persepsi mental juga? Bagaimana tentang kata-kata lain seperti kata-kata yang terkait dengan eksistensi atau wujud dalam arti sesuatu yang ada? Apakah kata-kata ini juga berkorespondensi dengan sejumlah persepsi mental yang ada di benak Anda ataukah tidak?
Untuk memudahkan diskusi, mari kita gunakan istilah wujud (existence) dan maujud (being).
Pertanyaan: Apakah kata ada dalam dua kalimat berikut: air ada dalam gelas dan api ada dalam kompor, merupakan ucapan tidak bermakna? Atau, apakah ia mempunyai makna yang khusus sebagaimana kata lainnya yang digunakan dalam dua kalimat tersebut? Nah, apabila istilah ada benar-benar memiliki makna khusus pada dirinya sendiri, apakah dan bagaimanakah kata tersebut diterapkan pada air dan api? Apakah fakta bahwa istilah ada digunakan pada air dan api sama-sama menandakan bahwa keduanya memiliki “sebuah kata umum” atau bahwa keduanya memiliki “sebuah pengertian umum”?
Barangkali lebih baik untuk menggambarkan apa yang kami maksud dengan memiliki “kata umum” atau “makna umum” dengan sejumlah contoh dari kehidupan biasa.
Anggaplah, seorang bayi lahir dari keluarga Anda dan Anda menamakannya Parviz. Anggap juga bahwa bayi lain lahir di lingkungan ratusan keluarga lainnya yang jaraknya ratusan mil di kota lain dan keluarga lain, dan mereka, tanpa mengetahui apapun tentang nama anak Anda, juga menamakan anak mereka, Parviz. Hal semacam ini, mengembangkan sebuah ikatan otomatis antara anak Anda dan anak lain, dan ikatan ini tiada lain disebabkan memiliki nama anak yang sama, yang semata-mata merupakan hasil dari cita rasa orangtua mereka.
Sekarang, apakah memiliki nama yang sama menandakan merniliki sesuatu yang lain sam juga? Biasanya tidak. Ia semata-mata merupakan persoalan cita rasa. Anda menjadi suka nama Parviz dan memanggil anak Anda dengannya. Orangtua lain juga menjadi suka nama Parviz dan memilihnya untuk putra mereka. Anda bisa jadi menyukai nama Parviz karena satu alasan; dan orangtua lain mungkin menyukai nama tersebut karena beberapa alasanlain. Bagaimanapun, menyandang nama Parviz yang sama tidak menandakan adanya karakteristik lain yang sama antara dua anak ini. Ini merupakan sebuah contoh dari pemilikan nama yang sama.
Bayangkanlah lagi, Anda memiliki bola putih salju dan kapur putih. Alasan bagi Anda untuk memberi label “putih” kepada kedua benda ini bukan disebabkan bahwa seseorang telah memilih secara sembarang dengan menamakan kedua objek itu “putih”. Alih-alih, ini merupakan suatu indikasi bahwa dua objek ini mempunyai kualitas sama satu sama lain. Dengan kata lain, kata “putih”, menunjukkan bahwa kedua objek ini memiliki “makna umum” yang diletakkan dengan cara lain. Dua objek ini memiliki kesarnaan warna, dan warna ini adalah “pengertian” di mana mereka mempunyai kesamaan. Lebih jauh, pemilikan “pengertian” yang sama ini merupakan sebab dari keduanya yang disebut “putih”.
Inilah mengapa ketika membahas objek-objek yang memiliki sebuah “kata yang sama”, setiap entri baru yang masuk ke dalam kelompok mesti dicapai oleh objek-objek yang mempunyai “pengertian yang sama”. Di sini, tidak ada proses penamaan baru yang penting.
Sekitar 14 abad yang silam seorang anak laki-laki lahir di keluarga Sasanid yang mereka namai Parviz. Jika sejak itu tidak ada keluarga lain yang memilih untuk memanggil nama anak lelakinya Parviz, maka nama ini niscaya menjadi sesuatu yang khusus milik Raja Sasanid, Khosrow Parviz.
Di sisi lain, jika ratusan anak-anak lahir dari keluarga lain dan semua anak ini memiliki karakteristik fisik dan psikologis yang sarna dengan Khosrow Parviz tapi orangtua mereka menamakan anak-anak mereka dengan nama lain, maka tak satu pun kemiripan bisa membenarkan anak-anak ini disebut Parviz dengan sendirinya. Kalaulah ada, amat sedikit anak lelaki yang menunjukkan kemiripan dengan Khosrow Parviz. Tentu saja, ini sama sekali tidak benar dari kata “putih”. Setelah menyebutkan salju sebagai putih karena warnanya dan fakta bahwa ia merefleksikan hampir seratus persen cahaya yang menerpanya, dengan sendirinya kita menyebut putih pada objek apapun yang memiliki kualitas-kualitas yang sama tanpa membutuhkan proses penamaan baru. Ini terjadi demikian karena kata “putih” mewakili persepsi mental yang umum atas subjek-subjek tersebut seperti kapur tulis, salju, dan seterusnya.
Sekarang, setelah memiliki satu “kata yang sama” dan satu “pengertian yang sama” yang secara jelas dibedakan dari satu dengan yang lain, kita bisa kembali ke pembahasan kita ihwal maujud (existent) dan mengulang dua pernyataan: “Ada api dalam kompor” dan “ada air dalam gelas”. Kita melihat bahwa sifat wujud atau “ada” (isness) disandarkan kepada baik api maupun air dan kedua-duanya ada. Dengan demikian, kata ada (existent) merupakan sesuatu di mana mereka berbagi satu sama lain, tidak seperti kata api atau air yang hanya bisa berlaku kepada salah satu di antara keduanya. Nah, kini pertanyaannya adalah: apakah fakta bahwa api dan air mempunyai “ke-ada-an” (isness) yang sama di antara keduanya yang menandakan bahwa dua objek ini mempunyai kata yang sama ataukah pengertian yang sama?
Apabila kedua objek tersebut memiliki “ke-ada-an” dalam pengertian umum yang sama, yang berarti kedua objek ini mempunyai “kata yang sama”, maka menyebut salah satu di antara keduanya sebagai objek yang ada (eksisten) menuntut proses penamaan yang terpisah. Sekarang, apa masalahnya?
Di pihak lain, apabila memiliki kata “is” yang sama di antara “air di dalam gelas” dan “api dalam kompor” yang berarti keduanya mempunyai “pengertian yang sama”, maka proses penamaan terpisah bukan hal penting. Ini akan berarti bahwa kita, bagaimanapun, harus memiliki persepsi mental yang bersesuaian dengan kata “is” yang berlaku pada air di dalam gelas dan api di dalam kompor. Persoalan tersebut dijawab dengan pertanyaan berikut: “apakah persepsi bersama ini dan darimanakah ia asalnya?”
Filsafat eksistensial mengawali analisisnya dengan upaya untuk memahami persepsi mental ini dan sumber objektifnya serta memegang pendapat tersebut bahwa melalui suatu analisis terhadap konsep eksistensi dan temuan dan akal untuk perkembangannya dalam pikiran kita, jalan-jalan baru untuk meraih pengetahuan tentang watak hakiki dunia ini dibukakan untuk kita. Inilah mengapa filsafat ini memula kata-katanya dengan menanyakan, apakah eksistensi sama dalam kata atau makna?
Jawaban yang diberikan para filosof eksistensial atas pertanyaan ini didasarkan pada penyelidikan dan analisis cermat mereka, yaitu, bahwa wujud (existence) adalah sama dalam pengertian kata vokal. Dengan kata lain, istilah wujud dan semua sinonimnya dalam bahasa lain, merujuk pada persepsi, konsep, dan pengertian mental yang tunggal yakni bahwa persepsi esensial dan konkret yang dialami dalam setiap persentuhan dengan realitas. Ini membantu untuk menunjukkan kepada kita bahwa wujud itu sendiri merupakan realitas tunggal yang ada dalam api dan air. Karena, apabila wujud bukan fakta tunggal yang dimiliki api dan air secara umum, niscaya ia tidak akan memunculkan persepsi tunggal yang diderivasikan dari air dan api.
Mulla Shadra memiliki pendapat demikian bahwa tidak perlu bagi kita untuk melewati jalan panjang dan pelik ini untuk memahami universalitas dan keunikan realitas wujud. Cukuplah bagi setiap individu realistik (mystic) peka dan berwawasan untuk mempertimbangkan persepsi pertama yang ia miliki, dari dunia aktual; untuk mengetahui reali.tas wujud itu sendiri. Apa yang saksikan dalam persentuhannya dengan fakta tertentu adalah, pertama-tama, wujudnya fakta itu. Hanya setelah itu, menentukan kuiditas objek yang dibahas. Dan apa yang dimaksud dengan kuiditas di sini adalah esensi dan jumlah kualitas yang manusia pandang dalam objek partikular ini namun gagal menjumpai, entah semua ataupun sebagian, dalam objek-objek lain.
Noktah yang menarik di sini adalah bahwa dalam setiap konfrontasi dengan realitas aktual, pengetahuan manusia akan eksistensinya, aktualitas, dan realitas, sama-sama jelas dan pasti kecuali ia terjerat dalam tarikan sofistik, sementara penangkapan seseorang akan kuiditas suatu objek bisa melibatkan ketidakpastian. Misalnya, ketika Anda melihat sesuatu dari jarak beberapa kilometer, Anda tak meragukan keberadaannya dan penangkapan Anda akan realitasnya adalah jelas dan pasti. Akan tetapi, pengetahuan Anda akan kuiditasnya tetap tidak jelas, dan Anda harus menunggu objek tersebut sampai Anda lebih dekat dengannya atau melihatnya melalui teropong, sebelum mendapatkan persepsi akan kuiditasnya secara relatif.
 0%
0%
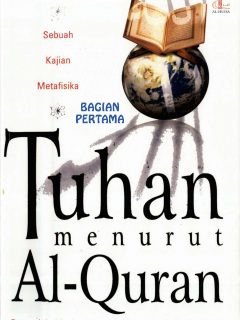 pengarang: AS-SHAHID SAYYID MUHAMMAD HUSAYNI BEHESTI
pengarang: AS-SHAHID SAYYID MUHAMMAD HUSAYNI BEHESTI